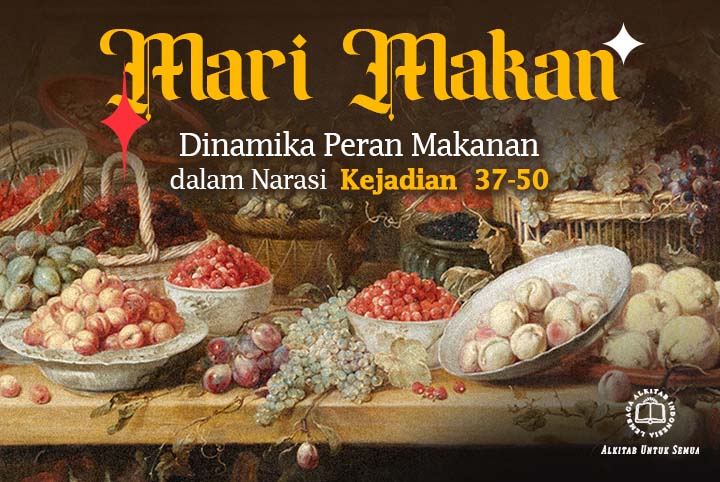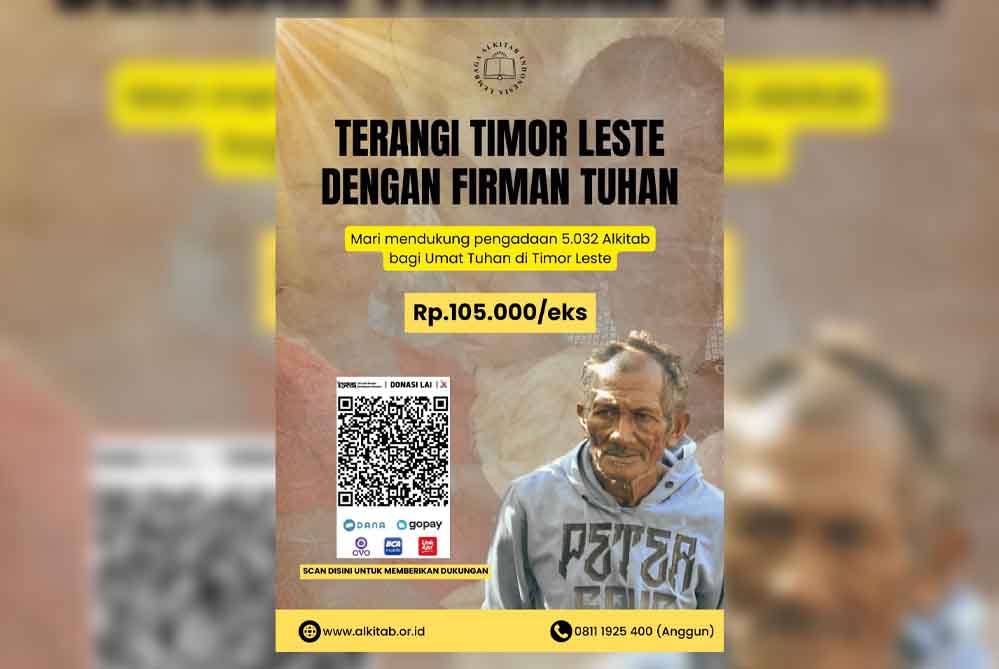Seminar Alkitab - Pdt. Ira Mangililo, Ph.D.
Kisah tentang Gundik Lewi dalam Hakim-hakim 19:1-30 merupakan salah satu narasi paling mengerikan dan mengganggu dalam seluruh Alkitab. Ia bukan sekadar kisah kekerasan terhadap seorang perempuan, melainkan potret mendalam tentang kehancuran moral, sosial, dan spiritual Israel pada masa ketika “tidak ada raja di Israel” (Hakim-hakim 19:1; 21:25). Dalam struktur naratif Kitab Hakim-Hakim, kisah ini menjadi semacam epitaf bagi bangsa yang kehilangan orientasi etis dan teologisnya. Di balik lapisan kisah ini, tersingkap dinamika kompleks mengenai tubuh, kuasa, gender, dan agama yang membentuk wajah masyarakat patriarkis Israel kuno.
I. Status Pileghesh: Antara Properti dan Subjek yang Hilang
Istilah פִּילֶגֶשׁ−pileghesh dalam Alkitab merujuk pada perempuan yang hidup bersama seorang laki-laki tanpa status hukum penuh sebagai istri. Ia bukan pelacur, tetapi juga bukan istri yang sah. Statusnya berada di ruang abu-abu antara pengakuan sosial dan keterpinggiran hukum. Dalam teks-teks seperti Kejadian 22:24; 1 Tawarikh 1:32; dan 2 Samuel 21:11-14, para pileghesh digambarkan sebagai perempuan yang berperan dalam reproduksi, politik, dan bahkan aksi moral, seperti Rizpah yang berani menuntut keadilan bagi anak-anaknya.
Namun, dalam dunia patriarkis Israel, nilai perempuan ditentukan oleh relasi-relasi maskulin di sekitarnya. Sebagai anak dari seorang ayah, milik seorang suami, atau alat untuk melanjutkan keturunan. Identitas otonom hampir tidak diakui. Dengan demikian, pileghesh dalam Hakim-hakim 19 adalah simbol konkret dari tubuh perempuan yang dipertukarkan, dinilai, dan dikorbankan dalam sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kendali.
Christine Mafana, seorang penafsir asal Amerika keturunan Zimbabwe, menjelaskan bahwa status rendah pileghesh kerap terkait dengan ketiadaan mas kawin yang sah. Ia menjadi perempuan “setengah diakui” dalam relasi rumah tangga, tanpa perlindungan penuh baik dari suaminya maupun dari masyarakat. Situasi inilah yang memperlihatkan betapa rapuh posisi sosial sang pileghesh di tengah sistem patriarki Israel kuno.
II. Pembacaan Naratif: Ambiguitas, Kekerasan, dan Keheningan
Narasi Hakim-hakim 19 dibangun dengan ketegangan yang meningkat secara perlahan menuju kekejaman yang tak terbayangkan. Para tokohnya tanpa nama: seorang Lewi dari Efraim, seorang pileghesh dari Betlehem, ayah perempuan itu, dan para penduduk Gibea. Seolah disengaja anonim. Ketiadaan nama ini menandakan universalitas dosa sosial dan kehilangan identitas moral umat Allah.
1. Kepergian Sang Gundik: Zanah atau Marah?
Ayat pembuka kisah ini menimbulkan perdebatan filologis. Teks Masoret menggunakan kata זָנָה (zanah−berlaku serong), sementara Septuaginta memilih ὀργίσθη (orgisthē−marah). Terjemahan LAI mengikuti versi Masoret, sedangkan NRSV mengikuti Septuaginta. Perbedaan ini penting, apakah perempuan itu meninggalkan rumah karena berzina, atau karena marah dan tersakiti?
Menurut J. Alberto Soggin, tidak ada bukti dalam teks bahwa perempuan itu bersundal; lebih mungkin ia meninggalkan suaminya karena mengalami kekerasan atau konflik rumah tangga. Susan Niditch dan Gale A. Yee menambahkan bahwa dalam masyarakat patriarkis, tindakan perempuan yang meninggalkan suaminya sering dilabeli sebagai “sundal” sebagai bentuk kontrol sosial terhadap otonomi perempuan. Dengan demikian, istilah zanah di sini lebih merupakan tuduhan ideologis ketimbang fakta moral.
2. Berbicara kepada hatinya: Upaya Rekonsiliasi Semu
Ketika sang Lewi mendatangi perempuan itu, teks mencatat bahwa ia hendak berbicara kepada hati (membujuk) perempuan itu (ayat 3). Frasa ini dalam Alkitab sering muncul dalam konteks penghiburan atau permintaan maaf (lih. Rut 2:2; Kejadian 34:4). Namun, tindakan sang Lewi kemudian menunjukkan bahwa rekonsiliasi ini tidak berakar pada kasih, melainkan pada rasa kepemilikan. Setelah “berdamai” di rumah ayah perempuan itu, sang pileghesh menghilang dari pusat narasi. Semua percakapan terjadi hanya di antara laki-laki: sang Lewi dan ayah perempuan itu. Sang perempuan kembali dibisukan, bahkan dalam narasi yang menuturkan kisah tragis hidupnya.
3. Tubuh tanpa Suara
Ketika orang Lewi bersiap kembali ke rumahnya, keputusan perjalanan sepenuhnya diambil oleh para laki-laki. Bahkan hamba laki-laki diberi suara dalam teks (ayat 11), sementara sang perempuan tidak. Dalam hermeneutika tubuh, suara adalah representasi kuasa. Ketika seorang tokoh dibungkam, ia direduksi menjadi objek naratif, kehadirannya hanya diakui melalui tubuhnya, bukan pikirannya. Dalam Hakim-hakim 19, perempuan hadir secara fisik tetapi absen secara verbal. Tubuhnya menjadi “teks yang dibaca” oleh para laki-laki, bukan “penulis” dari narasinya sendiri.
III. Kekerasan yang Mewujud: Dari Tubuh ke Bangsa
Klimaks cerita ini merupakan puncak horor moral Israel. Di Gibea, para lelaki setempat mengepung rumah dan menuntut agar sang Lewi diserahkan untuk diperkosa. Dalam dunia patriarkis, pemerkosaan laki-laki terhadap laki-laki bukan soal orientasi seksual, melainkan ekspresi supremasi dan penaklukan. Gale A. Yee menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki digunakan untuk “memfeminimkan” korban, menandakan penundukan total terhadap kehormatan dan identitasnya.
Demi menghindari “kehinaan” itu, sang tuan rumah dan sang Lewi justru menawarkan tubuh-tubuh perempuan: anak gadis tuan rumah dan pileghesh si Lewi. Tubuh perempuan dijadikan alat negosiasi moral antara laki-laki, menunjukkan bahwa dalam struktur sosial Israel, penderitaan perempuan masih lebih dapat diterima dibandingkan kehilangan kehormatan laki-laki. Dalam titik ini, teks menelanjangi wajah paling gelap dari patriarki: bahwa nilai tubuh perempuan diukur dari sejauh mana ia dapat “menyelamatkan” harga diri laki-laki.
Perempuan itu kemudian diperkosa semalaman. Tubuhnya dilemparkan di depan pintu, hanya tubuh yang membisu. Keesokan harinya sang Lewi menemukan dia tergeletak di ambang rumah, suatu simbol tragis dari perempuan yang hidup di “ambang” masyarakat: tidak sepenuhnya di dalam, tetapi juga tidak sepenuhnya diakui. Dan ketika sang Lewi tidak mendengar respon, dia mengangkat tubuh pileghesh dan menaikkannya di atas keledainya seperti hewan yang sudah tidak berdaya. Lalu dia melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, sang Lewi memotong tubuh pileghesh menjadi dua belas bagian dan mengirimkannya ke seluruh Israel, bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai propaganda untuk memicu perang saudara. Dengan demikian, tubuh perempuan itu kembali menjadi alat politik laki-laki.
IV. Teologi dari Abu: Tuhan di Tengah Keheningan
Kisah ini menantang kita dengan pertanyaan mendasar: di manakah Allah ketika tubuh perempuan dihancurkan oleh sistem yang seharusnya melindunginya? Narator Hakim-hakim 19 tidak menyebut intervensi Allah sedikit pun. Keheningan ilahi di sini bukan berarti ketidakhadiran, melainkan seruan bagi pembaca untuk menyadari keterlibatan manusia dalam menciptakan neraka sosialnya sendiri.
Teolog feminis, Phyllis Trible menyebut kisah ini sebagai “text of terror”, teks yang mengingatkan bahwa Alkitab tidak selalu menjadi kitab penghiburan, tetapi juga cermin penderitaan manusia yang dibiarkan oleh sistem dosa struktural. Di balik keheningan Allah, tersimpan panggilan bagi manusia untuk mengutuk kekerasan dan menghidupi keadilan.
V. Refleksi Kontekstual: Suara Perempuan di Tengah Dunia yang Membungkam
Kisah Gundik Lewi menghadirkan cermin tajam bagi dunia modern yang masih dilingkupi kekerasan berbasis gender dan sistem sosial yang membungkam suara perempuan. Narasi ini menyingkap bukan hanya tragedi individual, melainkan juga kehancuran moral komunitas yang kehilangan kepekaan terhadap penderitaan.
Ketika gereja membungkam suara perempuan atau membiarkan ketidakadilan berlangsung atas nama moralitas dan tradisi, ia sesungguhnya mengulangi dosa sang Lewi, mengorbankan tubuh dan martabat manusia demi menjaga citra diri. Karena itu, membaca Hakim-hakim 19 berarti menolak diam di hadapan penderitaan, serta mengubah “keheningan tubuh” menjadi “suara kenabian” yang menyerukan keadilan dan pemulihan.
Meski kisah ini berakhir dengan tubuh yang tercabik, iman kita tidak berhenti di sana. Dari kehancuran itu, Israel, juga dan kita saat ini, dipanggil untuk bertobat dari sistem yang menindas dan untuk memulihkan martabat manusia sebagaimana dikehendaki Allah Sang Pencipta, yang berpihak pada kehidupan dan menegakkan keadilan di tengah dunia yang terluka.