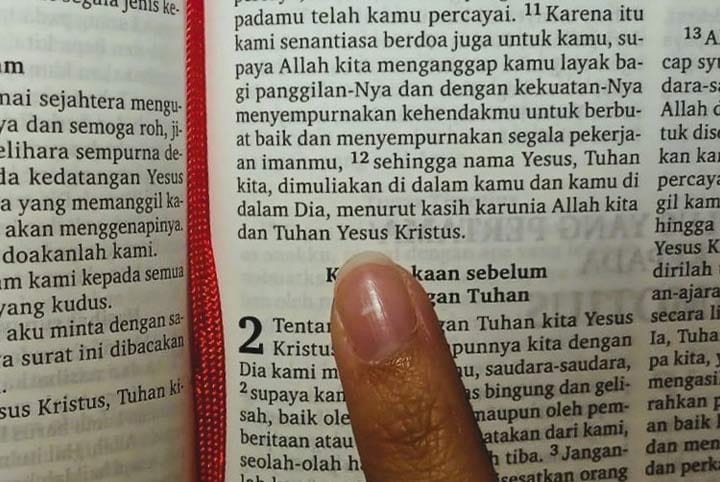Hidup manusia sering kali ditentukan bukan hanya oleh apa yang kita lihat, tetapi terutama oleh apa yang kita dengar dan bagaimana kita meresponsnya. Mendengarkan berarti bersedia membuka diri, tidak hanya sibuk dengan diri sendiri. Jadi, mendengar bukan sekadar aktivitas inderawi, melainkan melibatkan hati dan kesediaan untuk bertanggung jawab, tanggung jawab untuk menimbang, menyimpan, dan mewujudkan kebenaran yang telah didengar dalam tindakan nyata.
Itulah sebabnya Mazmur 78 dibuka dengan ajakan, “Hai bangsaku, arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku.” Ajakan ini bukan sekadar permintaan sederhana, melainkan undangan untuk membuka telinga, hati, dan hidup di hadapan Allah, serta menanggapi firman-Nya dengan kesetiaan dalam keseharian.
Mazmur 78:1–11 memperlihatkan tiga bagian penting. Pertama, ajakan mendengarkan (ayat. 1–4), di mana pengajaran diibaratkan sebagai ‘teka-teki dari zaman purbakala’ yang tidak boleh hanya lewat di telinga, tetapi perlu direnungkan dan dipahami. Kedua, perintah mewariskan iman kepada generasi berikutnya (ayat 5–8), menegaskan bahwa kesetiaan kepada Allah adalah warisan yang harus dipelihara bersama. Ketiga, contoh kegagalan umat (ayat 9–11), di mana suku Efraim yang lengkap persenjataannya justru gagal karena melupakan perjanjian Allah. Dari sini jelaslah bahwa kekuatan iman tidak ditentukan oleh kemampuan lahiriah, melainkan oleh kesediaan hati untuk mendengar dan mengingat karya Allah.
Mazmur ini juga menyingkap identitas. Penyebutan Efraim bukan sekadar catatan sejarah, melainkan juga penegasan teologis bahwa melupakan Allah berarti kehilangan arah hidup. Sebuah bangsa atau komunitas yang tidak mau mendengar dan tidak mau mengingat akan mengulang kegagalan leluhurnya. Maka dari itu, mengingat, baik keberhasilan maupun luka masa lalu, adalah bagian penting dari pembentukan iman. Ingatan kolektif itulah yang meneguhkan daya tahan spiritual dan moral umat Allah.
Sahabat Alkitab, pesan Mazmur ini tetap relevan bagi kita saat ini. Betapa banyak orang di zaman ini, meski diperlengkapi teknologi dan pengetahuan, tetap gagal menghadapi pergumulan hidup karena ‘telinga’ hatinya tertutup bagi suara kebenaran. Maka dari itu, mendengarkan firman bukanlah tindakan pasif, melainkan langkah aktif yang memampukan kita untuk tetap setia, rendah hati, dan berani mengemban tanggung jawab iman.
Mendengarkan berarti menolak melupakan, berarti berani menghadapi masa lalu, dan berarti mewariskan pengharapan bagi generasi mendatang. Maka, marilah kita membuka telinga, bukan hanya untuk suara manusia, melainkan terutama bagi pengajaran Allah yang membentuk hidup kita. Sebab iman yang sejati lahir dari kesediaan mendengar, dan kesetiaan hidup dipelihara melalui pengajaran yang diingat dan dipraktikkan.